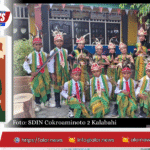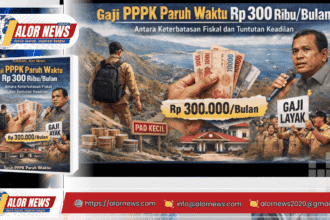Kalabahi, Alor News – Setiap 10 November, bangsa Indonesia kembali merenungi makna kepahlawanan. Bukan sekadar mengenang para pejuang yang gugur di medan perang, tetapi juga menilai kembali nilai-nilai perjuangan, kejujuran, dan pengorbanan yang membentuk wajah bangsa.
Tahun ini, peringatan Hari Pahlawan terasa berbeda. Di tengah semangat penghormatan itu, muncul kembali wacana pengajuan Presiden Soeharto sebagai Pahlawan Nasional—isu yang memantik perdebatan panjang di ruang publik.
Pertanyaannya, apakah jasa besar dalam pembangunan dapat menutupi sisi kelam sejarah kekuasaan?
Jasa dan Kontribusi Soeharto yang Tak Terbantahkan
Soeharto adalah tokoh sentral dalam sejarah Indonesia. Ia memimpin bangsa ini lebih dari tiga dasawarsa, melewati masa-masa sulit pasca 1965 hingga memasuki era pembangunan nasional. Banyak generasi yang tumbuh pada masa Orde Baru mengenang era itu sebagai masa keteraturan dan kemakmuran.
Di bawah kepemimpinannya, Indonesia menikmati stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Melalui program Repelita dan Pembangunan Lima Tahun, Soeharto mendorong kemajuan infrastruktur, memperluas akses pendidikan, dan mencapai swasembada pangan pada 1984, prestasi yang masih dikenang hingga kini.
Di bidang pendidikan, ia mencanangkan program Wajib Belajar Enam Tahun dan pembangunan SD Inpres secara masif. Ribuan sekolah berdiri hingga pelosok desa, membuka akses belajar bagi jutaan anak Indonesia. Berbagai kebijakan lain, seperti beasiswa, peningkatan kapasitas guru melalui PLPG, dan pembentukan IKIP, turut mendukung pemerataan pendidikan dasar hingga kini.
Soeharto juga memberi perhatian pada pembinaan nilai-nilai kebangsaan melalui program Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Program ini menanamkan nilai Pancasila sebagai filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski mendapat kritikan karena bersifat indoktrinatif, P4 berhasil menumbuhkan kesadaran nasional dan semangat cinta tanah air.
Di tingkat domestik, program transmigrasi dan pembangunan pedesaan melalui Inpres Desa Tertinggal turut mengubah wajah wilayah terpencil di Nusantara. Jejak pembangunan fisik dan sosial masih terasa hingga kini, terutama di pulau-pulau besar di luar Jawa.
Di bidang politik luar negeri, Soeharto meneguhkan posisi strategis Indonesia. Ia melanjutkan diplomasi politik bebas-aktif, memperluas kerja sama ASEAN, dan menjadikan Indonesia tuan rumah berbagai forum internasional bergengsi, meningkatkan citra bangsa di kancah global.
Luka dan Bayang-Bayang Kekuasaan
Namun, di balik keberhasilan itu, sejarah mencatat beberapa luka bangsa. Pemerintahan Orde Baru meninggalkan catatan kelam dalam hal kemanusiaan, mulai dari tragedi 1965, operasi militer di Timor Timur, hingga pembatasan kebebasan pers dan oposisi politik. Walaupun sebagian pihak berargumen bahwa kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan demi stabilitas bangsa dan negara.
Selain itu, praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menjadi penyakit kronis yang mewarnai penghujung kekuasaannya, hingga memicu krisis ekonomi dan kejatuhan rezim pada tahun 1998. Luka-luka itu bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi menjadi bagian penting dari pelajaran sejarah bangsa.
Menimbang Makna Gelar Pahlawan Nasional
Pemberian gelar Pahlawan Nasional bukan sekadar penghormatan simbolik, tetapi merupakan keputusan negara yang berlandaskan hukum. Dasar hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Undang-undang ini secara tegas mengatur syarat, kriteria, dan tata cara penganugerahan gelar tersebut. Pasal 25 menegaskan bahwa tindakan kepahlawanan harus ditunjukkan melalui pengorbanan luar biasa dalam mempertahankan keutuhan negara, melampaui panggilan tugas, dan memberikan manfaat besar bagi bangsa
Lebih lanjut, Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa “Gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada warga negara Indonesia yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah melakukan tindakan kepahlawanan atau memiliki jasa yang luar biasa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia.”
Sedangkan Pasal 30 mengatur bahwa penganugerahan gelar dilakukan melalui mekanisme ketat, diusulkan oleh masyarakat atau pemerintah daerah, diverifikasi oleh Tim Peneliti, Pengkaji, dan Penilai Gelar Pahlawan Nasional (TP3N) di bawah Kementerian Sosial, sebelum akhirnya ditetapkan oleh Presiden.
Dalam konteks pengajuan nama Soeharto, penting untuk meninjau unsur “jasa luar biasa” dan “keteladanan moral”. Meskipun undang-undang tidak secara eksplisit menyebut “keteladanan moral”, namun konsep ini tersirat dalam kriteria pemberian gelar. Penilaian tidak hanya mencakup jasa atau prestasi, tetapi juga integritas, dedikasi, dan keteladanan perilaku kepemimpinan.
Tidak ada yang menyangkal peran Soeharto dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas politik nasional, tetapi gelar Pahlawan Nasional juga menuntut rekam jejak yang bebas dari tindakan yang mencederai nilai kemanusiaan dan keadilan.
Apakah seorang pemimpin yang membawa kemajuan namun juga meninggalkan luka kemanusiaan memenuhi syarat sebagai Pahlawan Nasional menurut undang-undang ini?
Pertanyaan ini menjadi ruang refleksi publik agar gelar Pahlawan Nasional tidak kehilangan makna substantifnya sebagai simbol pengorbanan dan keteladanan sejati.
Refleksi
Soeharto layak dinobatkan sebagai tokoh penting dalam sejarah pembangunan nasional, namun penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepadanya tetap perlu kajian yang mendalam. Sebab, keputusan saat ini akan menjadi preseden moral dan standar bagi penilaian kepahlawanan di masa mendatang.
Jika ukuran kepahlawanan hanya dilihat dari capaian pembangunan tanpa menimbang sisi kemanusiaan, bukan tidak mungkin banyak tokoh yang berhasil secara ekonomi dan pembangunan namun memiliki catatan yang mencederai nilai kemanusiaan dan keadilan pun dianggap layak menyandang gelar Pahlawan Nasional.
Pertanyaannya, apakah gaya kepemimpinan Soeharto di masa-masa sulit itu dapat dimaklumi? Dilihat dari perspektif sejarah dan dalam konteks tertentu, beberapa langkah dan keputusan Soeharto dapat dipahami, namun hal ini tetap menimbulkan perdebatan mengenai dampak kemanusiaan dan nilai moral kepemimpinan.
Penutup
Hari Pahlawan seharusnya menjadi momentum untuk menegaskan kembali bahwa kepahlawanan sejati tidak lahir dari kekuasaan atau jabatan, tetapi dari keberanian menjaga nilai kemanusiaan dan kejujuran.
Bangsa ini tidak kekurangan tokoh besar, tetapi sering kekurangan teladan moral. Karena itu, di tengah hiruk-pikuk wacana gelar dan penghargaan, marilah kita meneladani pahlawan dalam makna yang lebih sederhana—menjadi manusia yang jujur, adil, dan berani berbuat untuk sesama.
Penulis: Redaksi Alor News
Foto: Arsip Nasional RI
Disclaimer
Tulisan ini disajikan sebagai refleksi sejarah dan analisis atas jasa, kontribusi, serta sisi moral dan kemanusiaan dalam menilai kepahlawanan.