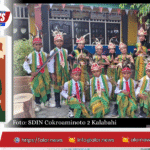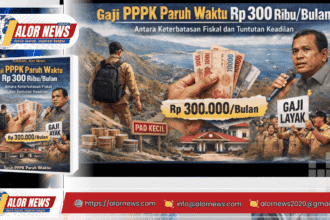Kalabahi, Alor News — Sekolah sejatinya bukan hanya tempat mentransfer ilmu, tetapi juga ruang membentuk karakter, nilai, dan kesejahteraan emosional peserta didik. Namun, dalam praktiknya, banyak sekolah di Indonesia masih berjuang menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan sosial-emosional siswa. Fokus pendidikan yang masih berat pada pencapaian akademik semata sering kali mengabaikan aspek sosial dan emosional, padahal keduanya merupakan fondasi keberhasilan belajar yang sesungguhnya.
Tulisan ini terinspirasi dari kegiatan Learning Cycle on the Use of Data for Education Policies yang diselenggarakan oleh KIX EMAP Hub dan PSPK di Bandung baru-baru ini. Dalam kegiatan tersebut, para pendidik, peneliti, dan pembuat kebijakan dari berbagai daerah, termasuk Nusa Tenggara Timur, berdiskusi tentang pentingnya mengoptimalkan pembelajaran sosial-emosional di sekolah. Penulis yang turut hadir dalam kegiatan itu menyaksikan langsung bagaimana semangat kolaborasi lintas daerah menguatkan keyakinan bahwa pendidikan sejati berakar pada keseimbangan antara hati dan pikiran.
Akibatnya, kita kerap dihadapkan pada fenomena perundungan (bullying), stres akademik, rendahnya motivasi belajar, hingga pudarnya empati di antara siswa. Jika dibiarkan, sekolah justru bisa kehilangan makna kemanusiaannya. Keberhasilan pendidikan tidak dapat diukur semata dari nilai kognitif, melainkan juga dari kemampuan siswa mengelola emosi, berinteraksi positif, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Di sinilah pendekatan Social-Emotional Learning (SEL) menjadi penting.
Mengapa SEL Penting?
Dalam pertemuan penyusunan policy brief yang diselenggarakan oleh KIX EMAP Hub dan PSPK di Bandung, isu Social-Emotional Learning (SEL) mengemuka sebagai salah satu topik strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Diskusi bersama para pendidik, peneliti, dan pembuat kebijakan menunjukkan kesamaan pandangan bahwa pendidikan yang berfokus hanya pada aspek kognitif tidak cukup membentuk pelajar yang tangguh, berempati, dan siap menghadapi tantangan sosial di masa depan.


Menurut Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL, 2020), SEL adalah proses pengembangan kompetensi sosial dan emosional melalui lima domain utama: kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Penelitian Durlak et al. (2011) menunjukkan bahwa penerapan SEL meningkatkan hasil akademik sebesar 11 persen dan menurunkan perilaku negatif di sekolah.
Temuan serupa dilaporkan OECD (2015), bahwa sekolah dengan budaya sosial-emosional yang kuat cenderung memiliki tingkat partisipasi dan prestasi akademik lebih tinggi. Artinya, suasana belajar yang sehat secara emosional dapat memperkuat capaian kognitif siswa—dua hal yang selama ini sering dipertentangkan.
Relevansi dengan Konteks Indonesia
Di Indonesia, konsep SEL sejalan dengan semangat Kurikulum Merdeka dan Profil Pelajar Pancasila yang menekankan keseimbangan antara karakter, kompetensi, dan kemandirian. Beberapa studi lokal memperkuat relevansi ini. Wibowo & Yuliana (2022) menemukan bahwa integrasi SEL dalam pembelajaran meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa SMP di Jawa Tengah. Sementara Prasetyo (2023) menunjukkan bahwa pelatihan guru berbasis SEL mampu menurunkan perilaku agresif dan meningkatkan kerjasama di sekolah dasar.
Namun, implementasi SEL di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Minimnya pelatihan guru, ketiadaan panduan implementasi nasional, serta budaya sekolah yang belum sepenuhnya mendukung kesejahteraan emosional menjadi tantangan besar.
Beberapa guru dari daerah seperti Alor, misalnya, menyampaikan bahwa pendekatan sosial-emosional sangat relevan diterapkan di sekolah-sekolah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas, tekanan akademik, dan keragaman sosial siswa. Bagi mereka, SEL bukan sekadar teori, tetapi kebutuhan nyata untuk menciptakan ruang belajar yang penuh kasih dan menghargai keberagaman.
Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi
Optimalisasi SEL tidak boleh dimaknai sebagai penambahan kurikulum baru. Sebaliknya, SEL harus diintegrasikan secara lintas mata pelajaran dan praktik keseharian di sekolah. Guru dapat menanamkan nilai empati, tanggung jawab, dan kolaborasi dalam setiap aktivitas belajar tanpa mengubah struktur kurikulum.
Langkah lain yang mendesak adalah penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berbasis praktik. Program peer mentoring dan community of practice dapat menjadi ruang berbagi pengalaman nyata penerapan SEL di kelas. Di sisi lain, Kementerian Pendidikan perlu mengembangkan instrumen nasional untuk memantau perkembangan sosial-emosional siswa sebagai bagian dari laporan mutu pendidikan.
Tidak kalah penting, sekolah harus menumbuhkan budaya positif dan kolaboratif, lingkungan yang menghargai perbedaan, memberi ruang aman bagi siswa mengekspresikan diri, serta melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. Kepala sekolah memegang peran kunci dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya kompetensi sosial dan emosional.
Penutup
Social-Emotional Learning sejatinya bukan program tambahan, melainkan investasi jangka panjang untuk membentuk manusia Indonesia yang utuh. Di tengah perubahan sosial yang cepat dan tekanan akademik yang tinggi, keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan emosional menjadi kebutuhan mendesak. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan pelatihan guru yang kuat, pendidikan Indonesia dapat bergerak menuju arah yang lebih manusiawi—membangun generasi yang bukan hanya pintar berpikir, tetapi juga pandai memahami dan peduli terhadap sesama.
Penulis: Hadi Kammis,dkk.
Fotografer: Dokumentasi Kegiatan PSPK–KIX EMAP Hub
Editor: Tim Redaksi Alor News